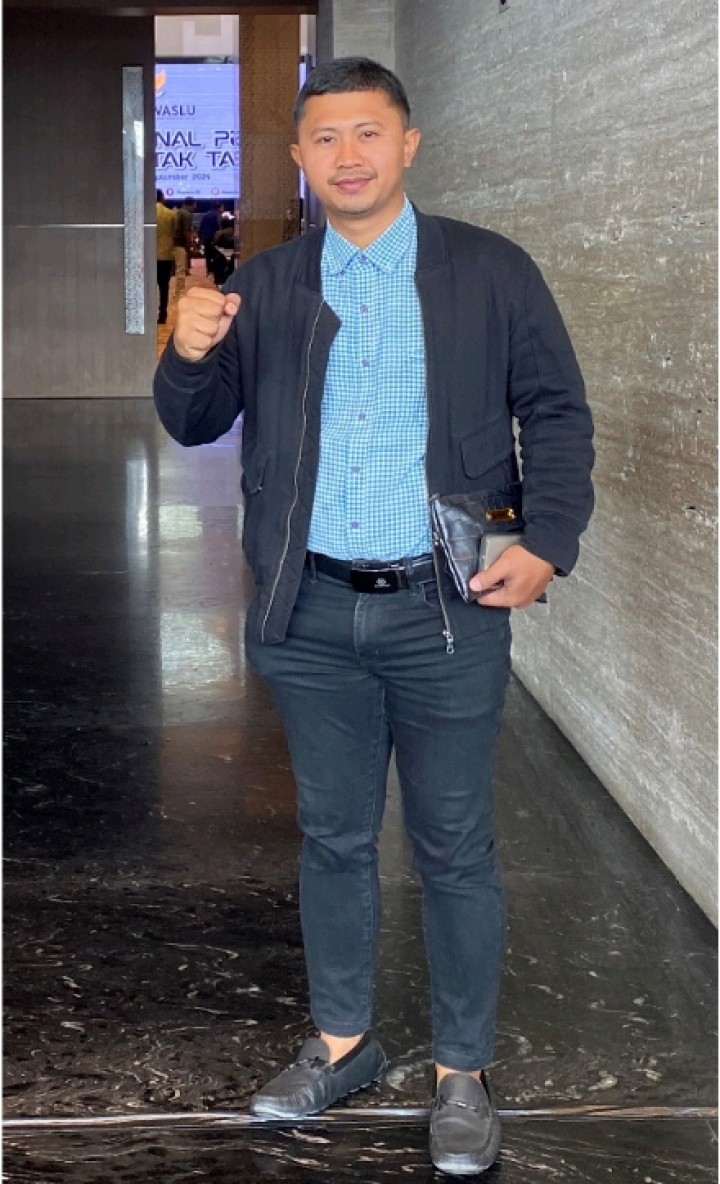RIAU24.COM - Demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini pasca reformasi memperlihatkan dinamika yang mengalami regresi demokrasi, meskipun ditengah kemajuan zaman, ekonomi, teknologi, dan kebudayaan ditengah masyarakat. Transformasi sosial demokrasi yang berlangsung sejak reformasi begitu cepatnya mengalami kemajuan dan tak luput mengalami juga regresi demokrasi yang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh kelompok atau golongan masyarakat yang memiliki kepentingan politik. Salah satu fenomena paling menonjol adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, yang selalu tarik menarik menimbulkan masalah hukum disebabkan dengan kepentingan kelompok atau golongan dalam kontestasi kedaerahan. Bukti nyatanya dalam aturan main pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024 yang lalu di beberapa daerah misalnya Kabupaten Tasik Malaya, Bengkulu Selatan dan Kutai Kartanegara yang sudah ditetapkan calon terpilih hasil coblosan, kemudian karena terjadinya ketidakpastian hukum aturan main sehingga di batalkan keterpilihannya.
Hukum menjadi benteng politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia agar memberikan keteraturan dan tidak sewenang-wenangan. Demokrasi tanpa hukum akan menjadi liar dan anarkis, sedangkan hukum tanpa demokrasi adalah kezaliman (Mahfud, Md: 2013). Namun bukan tanpa tantangan yang serius, bagi sistem hukum nasional karena dalam proses demokrasi sangat dipengaruhi oleh dimensi ekonomi, budaya, dan moral masyarakat sekaligus. Sehingga menimbulkan beberapa permasalahan mendasar salah satunya bagaimana negara mampu merumuskan model pemilihan kepala daerah yang adil, berkepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat?, yang tentunya pada akhirnya akan mewujudkan negara sejahtera (wefare state).
Untuk menjawab persoalan tersebut, tidak semudah membalikan telapak tangan, melainkan perlu adanya praktik nyata dan konstruktif yang di awali dengan perencanaan menyeluruh bersifat detail dan pelaksanaan yang konkrit lepas dari jerat kepentingan politik segelitir orang dan atau/ kelompok golongan. Paling tidak perencanaan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dapat dilakukan penelaahan secara filosofis multidimensional, yang didalamnya terdapat aspek Ontologis yakni hakikat eksistensi demokrasi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Aspek epistemologis tentang bagaimana kebenaran dan kesalahan demokrasi pemilu yang menjamin kedaulatan rakyat. Serta aspek aksiologis yang berhubungan dengan nilai-nilai moral dan tujuan sosial dari penegakan hukum itu sendiri terhadap persoalan demokrasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indoensia. Sehingga arah demokrasi pemilihan yang menjamin kedaulatan rakyat tidak hanya soal teknis perundang-undangan, tetapi juga refleksi filosofis tentang posisi dan peran ilmu hukum dalam tatanan ilmu pengetahuan apakah ia termasuk ilmu murni, ilmu dasar, atau ilmu terapan.
Dalam struktur keilmuan, hukum tidak dapat diposisikan sebagai ilmu murni sebagaimana Fisika atau Biologi yang berorientasi pada penemuan hukum alam yang bebas nilai (Paul Scholten, 2003). Sementara hukum, selalu berhubungan erat dengan manusia, masyarakat, dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum bersifat normatif dan preskriptif, hukum tidak hanya menjelaskan apa yang ada (das sein), tetapi juga menuntut apa yang seharusnya (das sollen). Pada titik inilah hukum ditempatkan dalam kategori ilmu dasar normatif, yakni ilmu yang berfungsi mengembangkan teori dan asas yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan praktik hukum. Namun, hukum tidak dapat berhenti di tataran teoretis saja, dalam praktiknya hukum bertransformasi menjadi ilmu terapan ketika asas-asas dan konsep-konsep yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, serta sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nyata.
Hukum sebagai ilmu Murni, Ilmu dasar dan ilmu terapan adalah bagian dari ilmu yang berdiri sendiri dan masing-masing bisa saling mempengaruhi satu dengan dengan yang lain. Ilmu dasar tentu memiliki arti bahwa ilmu dasar merupakan ilmu yang amat mendasar dalam khasanah keilmuan karena mengkaji fenomena alam secara sistematis untuk mengembangkan konsep dan prinsip, termasuk fisika, kimia, biologi, geologi, dan astronomi. Ilmu murni dikenal sebagai ilmu fundamental atau dasar ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memahami fenomena alamiah dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur alam semesta. Sedangkan ilmu terapan adalah ilmu pengetahuan yang berfokus pada penerapan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah praktis dan mengembangkan teknologi yang bermanfaat. Penelitian dalam ilmu terapan dilakukan dengan tujuan menghasilkan produk, layanan, atau solusi yang langsung bermanfaat bagi masyarakat atau industri.
Bila di komulatifkan, bahwa demokrasi dan pemilihan jika yang bertumpu pada ilmu dasar, hukum mengembangkan asas-asas seperti legalitas, kesalahan, dan pertanggungjawaban administrasi dalam proses administrasi pemilihan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Namun sebagai ilmu terapan, hukum dituntut untuk mampu menjawab persoalan empiris, misalnya bagaimana teori kepastian hukum itu terdapat dalam aturan proses pencalonan yang di implementasikannya sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang negatif. Dengan demikian, formulasi pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam konteks kepastian hukum aturannya menjadi ruang dialektika antara teori dan praktik, antara nilai dan kepentingan sosial.
Sedangkan ilmu murni dalam tradisi filsafat ilmu (Hans Kelsen, 2006), diorientasikan pada pencarian kebenaran universal tanpa mempertimbangkan manfaat praktis. Dalam ranah sosial, pendekatan ini mungkin hadir dalam bentuk analisis empiris atau statistik atas fenomena hukum tanpa keterlibatan nilai moral. Namun dalam hukum posisi seperti ini tidaklah memadai, hukum tidak mungkin berdiri netral terhadap realitas sosial karena hukum selalu diharapkan membawa keadilan (John Rawls, 2019) dan mengatur perilaku manusia (Annurriyyah et al., 2024). Ilmu murni hanya dapat berperan sebagai dasar pengamatan terhadap fenomena hukum, tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa suatu tindakan harus dianggap benar atau salah. Dengan kata lain, hukum tidak cukup dijelaskan oleh rasionalitas positivistik, tetapi memerlukan rasionalitas normatif yang menilai dan mengarahkan perilaku manusia.
Sebagai ilmu dasar hukum bergerak melampaui deskripsi menuju konstruksi. Hukum tidak sekadar mengamati realitas hukum melainkan membangun struktur normatif tentang bagaimana hukum seharusnya dijalankan. Teori hukum murni Hans Kelsen (Hans Kelsen, 2008), misalnya menjadi cerminan ilmu dasar yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang otonom. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dibebaskan dari campur tangan politik dan moral agar tetap objektif. Namun, pemikiran ini kemudian dikritik karena menjadikan hukum terlalu formalistik dan terlepas dari nilai keadilan sosial. Kritik inilah yang kemudian melahirkan pandangan baru bahwa hukum sebagai ilmu dasar tidak boleh tertutup, melainkan harus terbuka terhadap realitas kehidupan suatu konsep yang dikenal sebagai living law. Dengan demikian, hukum bertransformasi dari sistem statis menjadi sistem dinamis yang terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat.
Sebagai ilmu terapan hukum menunjukkan wajah praktisnya teori dan konsep yang telah dibangun dalam ranah ilmu dasar dioperasionalkan untuk menjawab persoalan konkret. Hukum menjadi instrumen kebijakan yang mengatur masyarakat, mengadili pelanggaran, dan menegakkan keadilan. Dalam konteks hukum adminitrasi dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ilmu terapan terlihat jelas dalam pembentukan undang-undang dan implemnetasinya dilapangan. Ilmu hukum yang tidak mampu menghasilkan terapan akan berhenti menjadi wacana normatif yang steril dari kehidupan. Karena itu, ilmu terapan hukum menuntut kemampuan reflektif dan adaptif untuk menerjemahkan teori ke dalam praktik yang hidup.
Kapan dan mengapa muncul keinginan melakukan terobosan dari ilmu murni ke ilmu dasar dan ilmu terapan dapat dipahami melalui dinamika sejarah keilmuan. Dalam filsafat ilmu, Thomas S. Kuhn menyebut fenomena ini sebagai krisis paradigma (Thomas S. Kuhn, 2020), yaitu ketika teori lama tidak lagi mampu menjelaskan realitas baru. Dalam hukum, krisis paradigma ini terjadi ketika teori kepastian hukum tidak memberikan rasa kepastian yang cendrung menimbulkan permasalahan multi tafsir dan tidak kongkrit sehingga hasil yang akan dicapai atas tidak adanya tidakpastian hukum maka akan bias cendrung hasil negatif yang menimbulkan banyak pertentangan dimasyarakat.
Sistem pemilihan yang mensyaratkan calon harus belum 2 periode jika ditelaah secara administrasi dan dikemas dalam hukum yang kongkrit, maka hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Tetapi jika dipaksakan oleh kepentingan kelompok atau golongan ketika terverifikasi dalam aturan mainnya terjadi adanya permasalahan dalam memaknai persyaratan calon maka akan terkoreksi hingga akhirnya dieliminiasi hasil tersebut. Atas peristiwa tersebut, maka seluruh elemen-elemen yang terkait dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka akan dirugikan. Belum lagi kepercayaan masyarakat terhadap alat kelembagaan negara dan para kontestan yang menelan banyak kerugian materil maupun inmateril. Terobosan keilmuan ini menandai bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, tetapi disiplin yang berevolusi seiring dengan perubahan masyarakat. Ketika hukum berhenti berkembang, ia kehilangan relevansi sosialnya. Sebaliknya, ketika hukum berani berinovasi dengan tetap berpijak pada asas moral dan keadilan, ia menjadi instrumen transformatif dalam kehidupan bangsa.
Dalam realitas hukum di Indonesia, muncul ketegangan antara das sollen dan das sein antara cita hukum dan kenyataan hukum (Achmad Ali, 2015). Idealnya, proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak menimbulkan banyak tafsir dalam persyaratannya, melainkan harus konkrit dan jelas. Namun kenyataannya, menimbulkan banyak tafsir dan tidak berpegang teguh pada asas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Misalnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Calon Wakil Walikota, menyebutkan
Pasal 7 Ayat (2) “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:…………. a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
Kemudian berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Calon Wakil Walikota, Pasal 19 menyebutkan :
“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan :
Jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
Masa jabatan yaitu:
1. Selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
2. Paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.
Pada pasal 19 huruf e tersebut yang menjadi perbedaan tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan. Karenanya putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mendiskualifikasi Calon Bupati terpilih di Tasik Malaya, Kutai Kartanegara dan Bengkulu Selatan akibat adanya suatu keadaan yang tidak memenuhi syarat dalam proses pencalonannya yaitu dinyatakan sudah 2 (dua) periode. Salah satu alasan dinyatakan sudah 2 (dua) periode adalah terkait dengan jabatan sementara dalam bentuk Pelaksana Tugas (Plt) yang menurut Mahkamah termasuk jabatan sementara yang dihitung masa jabatannya tidak harus berdasarkan sejak dilantik.
Jika ditilik maka dapat disimpulkan penyebab konflik tersebut adalah akibat peraturan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang multitafsir soal persyaratan periodesasi, sehingga karena aturan yang tidak konkrit dan bias hal ini cerminan pertentangan antara kemauan masyarakat yang menuntut keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan kemauan penguasa yang berupaya mempertahankan kekuasaan serta melindungi kepentingan politiknya.
Pertentangan antara das sollen dan das sein menunjukkan adanya jurang epistemik antara teori dan praktik. Di tingkat normatif, proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berorientasi pada cita kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, namun dalam implementasinya sering kali tersandera oleh kepentingan pragmatis. Akibatnya, hukum kehilangan legitimasi moralnya di mata public (Joseph Raz, 1979). Masyarakat merasakan ketidakadilan karena dalam proses pencalonan mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah sangat melelahkan dan bahkan menguras tenaga dan biaya politik yang tidak sedikit. Kesenjangan ini menunjukkan adanya legal gap dalam kebijakan formulasi proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dalam perspektif teori kepastian hukum Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah, pertama, adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula. Kedua, hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undanga. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.
Dari perspektif filsafat ilmu, kebijakan formulasi hukum dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi tiga dimensi utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menyoal hakikat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai subjek hukum, epistemologi menyoal cara mengikuti aturan maen dalam proses pencalonan, sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum pemilu dan demokrasi. Kebijakan hukum yang baik harus menyeimbangkan ketiga aspek ini. Jika hukum hanya berorientasi pada norma tanpa memperhatikan nilai keadilan, maka ia akan menjadi instrumen kekuasaan. Sebaliknya, jika terlalu berorientasi pada nilai tanpa kepastian hukum, ia akan kehilangan daya mengikatnya.
Kombinasi terintegrasi antara das sollen dan das sein menjadi prinsip utama reformasi demokrasi pemilu. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi Pembaruan kebijakan formulasi dalam proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : Pertama, adanya pengaturan yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam pencalonan khususnya soal pemaknaan periodesasi. Kedua, Penyelenggara Pemilu yang mandiri dan berintegritas menjadi harapan utama dalam proses penegakan administrasi pemilu, Ketiga, upaya hukum yang memadai dalam proses penegakan administrasi sehingga tidak mesti harus berproses di akhir, tetapi dalam tahapan pemilu bisa dilakukan upaya hukum administrasi yang konkrit dan konklusif. Dengan demikian, hukum yang baik tidak hanya tunduk pada teks undang-undang, tetapi juga mengabdi pada keadilan substantif.
Pengaturan soal pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bias pada akhirnya mencerminkan perjalanan ilmu hukum dari ilmu dasar menuju ilmu terapan, dari teori menuju perbaikan hukum, dari norma menuju realitas. Evolusi ini menunjukkan bahwa ilmu hukum tidak boleh berhenti pada tataran teks, melainkan harus terus bergerak untuk menjawab tantangan zaman. Seperti dikatakan Paul Scholten, hukum harus terbuka terhadap kehidupan agar tetap relevan bagi masyarakat yang diaturnya. Ketika hukum berhenti mendengar denyut nadi kehidupan sosial, ia kehilangan jiwanya dan berubah menjadi alat kekuasaan semata.(*)
Oleh:Muhamad Andi Susilawan, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas/ Anggota Bawaslu Kabupaten Siak