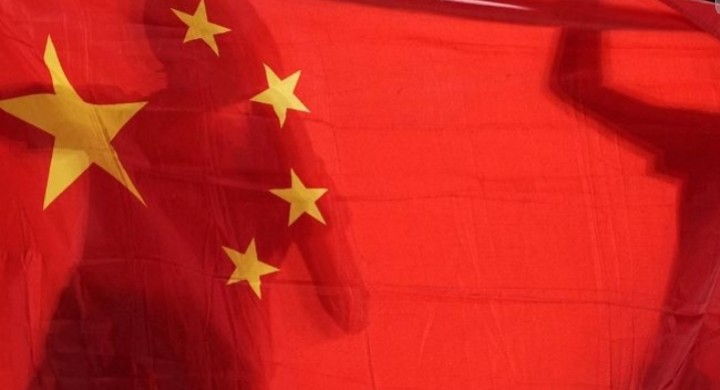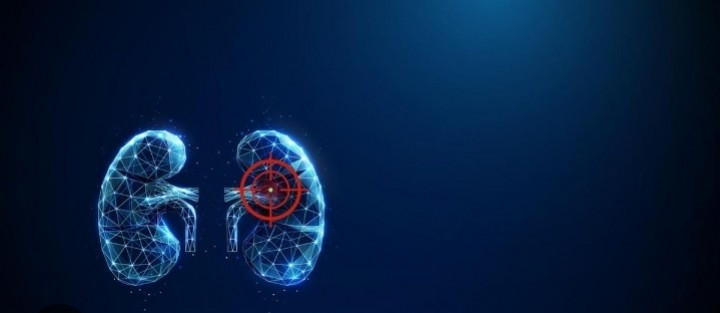RIAU24.COM -Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan di bawah bayang-bayang ekspektasi besar.
Target ambisius pertumbuhan ekonomi delapan persen, deretan mega-proyek strategis, dan janji memulihkan keadilan sosial sempat memantik optimisme publik.
Namun di tengah euforia itu, pengamat politik Rocky Gerung menjadi salah satu suara yang konsisten menyuarakan nada berbeda.
Sejak hari-hari pertama pemerintahan baru, Rocky menegaskan bahwa yang paling menentukan bukan sekadar angka dan proyek, melainkan narasi, struktur, serta mentalitas elit yang menjalankan pemerintahan.
“Ngapain kita evaluasi Presiden Prabowo? Yang mestinya dievaluasi adalah metodologi dari lembaga survei yang kosong dari idealisme,” ujar Rocky dalam Kuliah Terbuka bertajuk “Menguji Republikanisme di Indonesia” di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Rocky menilai, berbagai metodologi survei yang digunakan saat ini gagal memasukkan prinsip kesosialan manusia sebagai bagian penting dalam riset sosial.
Akibatnya, lanjut Rocky, persoalan bangsa yang seharusnya bersifat ideologis justru direduksi menjadi sekadar persoalan matematis. Opini publik, kata dia, seolah-olah bisa dibentuk dan dikendalikan lewat angka-angka statistik.
“Macam-macam survei itu tidak ada satu pun yang menguji prinsip kesosialan manusia dalam metodologinya,” tegasnya.
“Semua ide yang kita investasikan di awal kemerdekaan untuk menghasilkan republik seharusnya disimpan sebagai problem ideologis, bukan problem matematis. Akibatnya, opini publik dipaksakan dari atas,” ungkapnya.
Kritik Rocky terhadap lembaga survei itu berawal dari pembahasannya mengenai data ekonomi yang menunjukkan rata-rata tabungan masyarakat Indonesia kini hanya tersisa sekitar Rp1 juta. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan pergeseran dari market economy (ekonomi pasar) yang berorientasi pada efisiensi menuju market society (masyarakat pasar) yang didominasi logika pasar dalam hampir semua aspek kehidupan.
Menurut Rocky, kondisi ini membuat masyarakat Indonesia kehilangan kemampuan untuk menilai nasibnya sendiri karena terbuai oleh “sensasi statistik”.
Dalam bagian lain, Rocky menyoroti mekanisme evaluasi politik yang menurutnya masih bersifat internal dan seremonial. Ia menilai, pemerintahan modern kerap menilai dirinya sendiri melalui laporan kinerja dan survei popularitas, alih-alih membuka ruang koreksi publik.
“Yang mengevaluasi Presiden itu rakyat, bukan Presiden mengevaluasi dirinya sendiri,”
tegasnya.
Baginya, masyarakat sipil seharusnya berfungsi sebagai auditor eksternal kekuasaan.
“Protes rakyat itulah audit terbaik,” ujarnya lagi.
Namun, realitas politik hari ini menunjukkan kecenderungan sebaliknya: opini publik dikonstruksi oleh lembaga survei, media partisan, dan strategi komunikasi digital.
“Opini publik sekarang dikuasai narasi elit. Rakyat kehilangan otonomi berpikir,” tambah Rocky.
Dalam konteks yang lebih luas, kritik ini mengingatkan pada risiko “demokrasi prosedural tanpa substansi”: negara terlihat demokratis, tetapi sesungguhnya dikendalikan oleh opini dan persepsi buatan.
Demokrasi kehilangan fungsi deliberatifnya, dan rakyat berubah menjadi penonton politik, bukan pelaku.
Feodalisme Baru di Era Digital
Lebih jauh, Rocky menyebut Indonesia sedang menghadapi bentuk kekuasaan baru: feodalisme digital.
Di masa lalu, feodalisme ditandai oleh ketaatan terhadap bangsawan; kini, ia hadir dalam bentuk followers, likes, dan popularitas algoritmik. Ia menilai, sebagian elit politik tumbuh dari ruang digital, membangun citra tanpa kedalaman gagasan.
“Kita mencari pemimpin, tapi yang kita temukan hanya pemimpin yang paham teknis, tapi tidak punya dasar etis untuk memimpin,”
kata Rocky.
“Euforia palsu ini menular. Kita hidup di era di mana orang lebih sibuk memelihara follower daripada memperjuangkan gagasan,”
ujarnya.
Konsep “demokrasi kosmetik” yang ia sebut menjadi simbol zaman: tampak berwarna di permukaan, namun kosong di dalam.
Politik kehilangan akar etik, digantikan oleh logika pencitraan.
Pesimisme Rasional dan Tanggung Jawab Intelektual
Rocky menutup analisanya dengan refleksi yang lebih filosofis. Ia menolak disebut sinis; menurutnya, kritik bukan bentuk pesimisme, tetapi ekspresi tanggung jawab rasional.
Bagi Rocky, “pesimisme rasional” adalah cara menjaga kejujuran berpikir di tengah euforia pencitraan. Ia mengingatkan bahwa ukuran kemajuan bangsa bukanlah angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana rakyat memerdekakan pikirannya.
“Pesimis yang rasional lebih baik daripada optimis yang irasional,” ujarnya.
“Evaluasi pemerintahan bukan soal angka pertumbuhan,” katanya, “tapi tentang apakah bangsa ini masih memerdekakan pikirannya.”
Refleksi: Negara yang Gemuk, Ideologi yang Kurus
Setahun pemerintahan Prabowo adalah bab awal dari lima tahun perjalanan politik nasional. Namun sebagaimana diingatkan Rocky, tanda-tanda awal cukup untuk membaca arah sejarah.
Jika kekuasaan semakin padat tetapi ideologi kian menipis, bila kabinet berubah menjadi parade kepentingan, dan bila masyarakat sipil kehilangan fungsi kontrolnya, maka krisis legitimasi hanya tinggal menunggu waktu.
“Yang mengevaluasi Presiden itu rakyat, bukan dirinya sendiri,” ujar Rocky, menutup refleksinya.
Dalam konteks demokrasi Indonesia yang sedang bernegosiasi dengan populisme dan pragmatisme, kritik itu menjadi pengingat. Bahwa negara bisa tumbuh besar secara struktur, namun kehilangan makna secara jiwa.
Di antara deretan proyek, statistik, dan strategi komunikasi, pertanyaan paling penting tetap sama: apakah kekuasaan hari ini masih berpihak pada rakyat, atau justru pada dirinya sendiri?
(***)